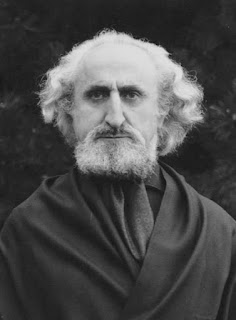 |
| Frithjof Schuon |
“Barangsiapa bertindak keterlaluan, pasti akan menyimpang dari kebenaran”—Imam Ali, Karramallah Wajhah
AGAMA—terlebih agama yang dikenal dan dikukuhkan manusia sekarang—datang dari dua arah ranah: langit dan bumi. Dari dua arah dan ranah ini subjek dan objek silih berganti. Ada kalanya subjeknya Tuhan dan objeknya manusia—atau subjeknya manusia dan objeknya Tuhan. Kedua hal ini berpengaruh pada satu persepsi mengenai sentrisme: entah itu antroposentris atau logosentris. Karenanaya jika logika yang digunakan oposisi biner, maka implikasi yang mengikutinya juga akan mengkutub di satu bilah.
Dalam skema logosentris, yang menjadi sentral adalah Tuhan. Agama dimaksudkan semata-mata untuk meraih singgasana keilahian semata. Jikapun yurisprudensi ditata dan hukum diatur semata-mata untuk memistari laku manusia. Segala sesuatu yang tak pas dengan kehendak yurisprudensi itu dipapakkan sedemikian rupa. Manusia dengan segala diversitasnya—baik secara mental dan spiritual—adalah nista adanya: produk sebuah tingkatan eksistensi rendah. Oleh karena itu, manusia adalah abdi Ilahi. Titik! Agama adalah produk baku, padat dan siapguna.
Lain hal jika antroposentris. Pusat adalah manusia, sebab itu Agama turun atau timbul ke permukaan disebabkan oleh urgensitas manusia. Agama adalah jawaban dari kebutuhan manusia pada yang Ilahi. Jika selama ini manusia banyak menemukan di lingkungannya sebuah kaos, berupa ketaktertataan, maka ia akan meninjau ke luar dirinya dan mencari kosmos. Artinya, manusia merindukan sebuah ekuilibrium kosmologis yang melampaui kehidupannya yang terlampau kaos.
Tapi titik pusat adalah manusia. Jika kemudian agama ada—sejauh tatapan antroposentris ini—maka ia hanya sebuah garis yang tak tegak lurus. Jika ada garis dan batas, maka ia harus sesuai dengan apa maunya manusia. Di sini agama berdinamika dengan semua perubahan pada manusia. Demikian pula dengan yurisprudensi, terus diubahsuai. Tidak hanya sebatas itu, Tuhan sebagai satu cita-cita luhur direkonstruksi, atau bila perlu didekonstruksi. Semakin reduktif Tuhan, semakin subtil manusia bisa mengenalnya.
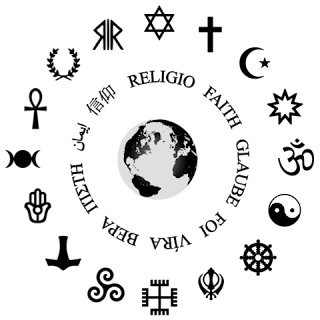 |
| Agama-Agama |
Kemudian implikasi dari kedua pengkutuban ini akan tampak pada bagaimana agama bekerja sebagai sebuah tata dan cara dalam kehidupan. Jika kita meninjau ujung dari kutub logosentris, kita akan menemukan tatanan sosial yang baku, kaku dan tak pandang bulu. Bagaimanapun manusia tak bisa bernegosiasi mengenai tatanan Ilahiyah yang datang sebagai hukum. Dari jihat ini kita akan menemukan darah dialirkan demi agama, demi Ia yang singgasana-Nya hanya bisa dijangkau oleh pekik pada liyan, oleh seruan yang kadang hanya bisa diterjemahkan oleh gada, hunus dan berangus. Di titik ini, agama jadi sesuatu yang semena-mena.
Sedangkan ujung dari antroposentris, kita akan menemukan bahwa agama adalah alat. Sifat sebuah alat tak lebih unggul dari penggunanya: manusia. Manusia mencari Tuhan, tapi sejak semula ia menuhankan dirinya sendiri dengan kemutlakan relatif. Agama, karenanya menjadi relatif, juga Tuhan dan hukum yang menyertainya. Manusia mengangankan sebuah kosmos yang dirumuskan sejak semula oleh kaos. Titik beku (dead lock) dari kutub ini adalah sebuah fenomena sahihnya segala hal. Desakralisasi pada tatanan Ilahi yang—tentu saja tak tepermanai—adalah tanda fenomena sosialnya.
Kekeramatan, khidmat, dan kerendahdirian pada keindahan (beauty), kontemplasi dan kesabaran, sebagai gerbang dan Ibu bagi kelahiran manusia ke dunia Ilahi yang kosmos terkikis dan putus. Di hadapan mata seorang antroposentris naif, waktu adalah segala-galanya. Simultanitas tak terbatas dari waktu menyegerakan dan menggerakkan manusia untuk berlaku produktif di hadapan dunia-realitas. Di titik ini, rahim agama yang di dalamnya terdapat kesakralan yang di antaranya: waktu suci, ruang suci, tindakan suci dan ucapan suci—boyak dan koyak. Dari ranah ini tak akan terlahir tatanan realitas yang solid, karena agama adalah angan-angan.
Kedua paradoks yang penulis kemukakan di atas adalah wajah agama sekarang ini. Kebingungan dasariah ini sudah tak lagi wajar, karena menyita aspek fisik lebih banyak dan perhatian lebih dari setiap manusia. Di sini tak ada pengecualian bahkan bagi mereka yang tak masuk dalam kategori beragama. Bagaimanapun apatisme dan syakwasangka akan memperrumit kejernihan yang musti ditempuh demi sebuah ekuilibrium: berkenaan dengan dua paradoks besar ini. Spiritualitas yang diharapkan berperan sebagai jantung pertemuan antara Tuhan dan manusia sedang diambang punah. Hal ini disebabkan oleh deras dan semakin mengkristalnya dua kutub di atas tadi. Agama ramah selalu dibantah oleh agama marah. Manusia juga selalu terjebak oleh kategori yang dibuatnya sendiri. Tapi juga kita tak selalu setuju dengan arus posmodern yang serba relatif itu.
Agaknya, persoalan kita di zaman ini bukan perkara bagaimana agama jadi ramah, atau manusia jadi tak berlebihan. Melainkan sebuah masa dimana setiap orang musti mencari satu kata “pas” yang bukan semata-mata relatif dan karenanya tiap orang jadi benar. Tapi sebuah “pas” yang teduh dimana manusia bisa bernaung, entah dari kesemena-menaan agama dan atau dari manusia itu sendiri. Yakni sebuah “pas” yang telah ada sejak permulaan jagat tercipta sebagaimana QS: 25: 2. Dimana “pas” ini adalah, sebagai apa yang oleh Frithjof Schuon katakan: pertemuan antara Tuhan sebagaimana adanya, dengan manusia sebagaimana adanya.[]
Penulis : Syihabul Furqon
Tahun : 2016












Posting Komentar