 |
| Don Quixote |
Cerita Don Quixote - Di abad-abad silam, sahibul hikayat Seyyed Ahmad Benengeli mengisahkan perjalanan kekesatriaan yang luhur—atau bisa kita anggap konyol dan sia-sia—yang secara baik diteruskan dan dicatat oleh Miguel De Cervantes. Epik majenun-imajinatif Petualangan Don Quixote tentu saja bukan hanya sekedar cerita sebelum tidur bagi anak-anak—bahwa sejatinya buku merupakan pemantik bagi imajinasi. Lebih dari itu, petualangan yang ditempuh Quixote adalah kesedihan (seperti diungkapkan Goenawan Mohammad) dan juga perayaan atau tepatnya karnaval kegilaan. Orang-orang di zaman ini akan mengidentifikasinya sebagai gejala Posmodernisme. Yakni suatu sikap dimana yang banal dirayakan tapi sekaligus simptom skizofrenik juga ikut meluap. Anehnya Quixote tak melulu berada dalam waham dan syakwasangka. Ia memegang satu pendirian unik, jika tidak dikatakan iman. Dalam hal ini iman bagi Don Quixote de La Mancha adalah ketulusan hati, rasa welas, cinta yang tulus, dan derma, juga ikhlas pada takdir kesatria.
Pun tak ada yang menyangkal bahwa dalam hal-hal tertentu kegilaannya mirip Majenun pada Layla atau Gibran pada Salma, atau Sandip pada Bimala: atau mungkin justru bermula dari satu akar tradisi Benengeli sendiri. Yang pasti, Don Quixote merupakan representasi dari kematian (death) dan kehidupan kembali (resurrection). Yang mati di hikayat itu adalah kemandekan yang juga berarti kebuntuan. Sedangkan yang bangkit adalah kebebasan dan keliaran eksistensial.
Dalam diri manusia tentu kia mengenal kematian eksistensial dimana tubuh tak lagi dialiri darah dan ditinggal nyawa. Tapi ada mati yang lain, yakni kemandekan. Yaitu fase dimana tak ada lagi sesuatu yang menarik untuk dijalani. Realitas monoton dan itu-itu saja, tak ada transformasi apa lagi revolusi. Laku sehari-hari kehilangan ruh dan girahnya. Imajinasi padam sama sekali dan manusia berada pada level kegelapan.
Karena itu wahyu perlu turun (revelation). Dalam hikayat Don Quixote wahyu tentu bukan kepak sayap malaikat Jibril yang memekakan telinga. Wahyu yang diturunkan Tuhan pada Don Quixote adalah tanda dan kelakar. Tak dipungkiri bahwa manusia sesekali perlu untuk menertawakan parilakunya, tindakannya. Don Quixote berdiri dan menari di atas panggung itu. Hikayatnya sendiri adalah wahyu bagi manusia yang sejatinya diliputi tindakan gawal. Karena Tuhan adalah kasih itu sendiri maka ia mengetengahkan Don Quixote untuk menjadi salah satu tanda dan suar. Maksudnya adalah bahwa hanya dalam Iman yang seliar Don Quixote lah kita akan menemukan tualang yang hidup, berdarah dan berdaging. Dalam bahasa kita sekarang: petualangan yang greget. Maka, Don Quixote de la Mancha menghidupkan apa yang sebelumnya mati: imajinasi, kejutan, gairah, spontanitas, cinta, petualangan dan buku (yang dianggap terkutuk) tentu saja. Jika dilihat dari kacamata orang biasa (baca: waras), tak ada yang baru dalam tindakan segila Don Quixote. Tapi jika kita masuk sedikit ke dalam, Don Quixote dengan tindakannya menawarkan satu perspektif baru. Yakni melihat segalanya dengan kacamata proses kebaruan. Setiap hal adalah baru dan karenanya tindakannya juga baru: meski tujuannya sama.
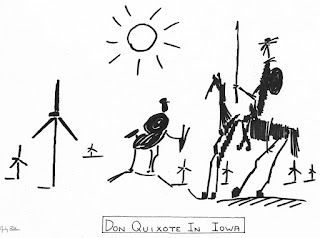 |
| Don Quixote |
Tapi bisakah kita membayangkan bagaimana Don Quixote berpetualang tanpa Sancho dan kudanya, Rozinante yang gagah? Hikayat itu dengan jeli menyematkan Sancho dalam lakon Quixote. Bukan untuk apa-apa selain melengkapi kegagahan dan kegarangan tekad Don Quixote dengan kecintaan Sancho pada kedamaian. Saya akan menukil satu cuplikan bagaimana Don Quixote menghendaki sikap keberanian dan Sancho menampilkan sikap kasih:
“Tuan, aku bukan orang yang suka berperang, seperti anda, tetapi orang yang cinta damai, mungkin seperti seorang suami dan ayah yang baik. Mohon catat itu dari sekarang bahwa aku akan memaafkan semua orang, yang telah atau akan, menjadi musuh-musuhku, apakah mereka bangsawan, raja, atau orang biasa.”
Don Quixot gerah mendengar semua ini. “Apa kau pengecut! Bagaimana kau bisa memimpin sebuah pulau atau karajaan? Seorang pemimpin besar harus tidak takut pada apa atau siapa pun.”
Dari sana kita melihat bahwa memang kedua petualang itu saling melengkapi. Dimana yang satu bersemangat untuk mendobrak ke sana dan ke mari sedang yang yang satunya lagi menenangkan dobrakan itu. Terlepas dari kenyataan bahwa Don Quixote gila dan Sancho mengetahui kegilaannya, Sancho tetap mendampingi Don Quixote. Pertanyaan demi pertanyaan muncul jika kita mengikuti cerita ini, karena memang itu tujuannya: membangkitkan pertanyaan. Hikayat ini bukan saja mengemukakan gagasan yang nyeleneh, tapi juga menularkan imajinasi itu sendiri.
Di awal cerita, kita akan menemukan bahwa seolah-olah imajinasi adalah sesuatu yang terkutuk dan mengantarkan pada kegilaan dan penderitaan. Kemuakan pada narasi awal cerita ini mungkin dialami para pembaca dan memutuskan untuk berhenti. Karena buat apa, toh isi ceritanya hanya kelakar dan olok-olok pada hidup yang teratur, tenang, meski tanpa gairah sama sekali. Kesabaran dibutuhkan untuk membaca hikayat konyol ini—tentu saja dengan sejumlah imajinasi yang aktif dan liar untuk mengimbangi kegilaan kisah petualangan Don Quixote sendiri.
“Hidup memang selimbur kejutan.” Demikian Sancho berujar pada Don Quixote. Dan kita, pembaca, juga menemukan cerita itu meledak-ledak penuh kejutan, penuh dengan semangat. Ada yang coba dihidupkan dari diri manusia, dibangkitkan. Menghidupkan sesuatu yang mati bukan perkara mudah, darah hanya menyatu dengan darah. Karenanya kisah berdarah-darah ditonjolkan. Pertanyaan lagi; apa yang mati dalam hikayat ini selain realitas yang menjadi banal dan tanpa gairah? Jawabannya tergeletak begitu saja ketika kita masuk dalam cerita: buku. Kita tahu bahwa buku bukan hanya benda mati dalam kisah ini, tapi justru yang sangat berperan dalam keseluruhan cerita. Sebuah buku adalah gerbang dunia, kata beberapa orang. Di dalamnya termaktub lebih dari selaksa pengetahuan, lebih dari tumpukan asumsi dan lebih dari sekedar imajinasi.
Jika dikatakan bahwa sebuah buku memiliki realitasnya sendiri. Ya, Don Quixote menampilkan itu. Jika dikatakan bahwa buku merupakan sumber pengetahuan—bahkan membentuk sikap. Jawabnya, ya, karena Don Quixote menunjukkan itu. Jika dikatakan bahwa buku juga terkutuk karena mengajarkan manusia untuk berimajinasi liar, mencoba hal yang baru. Jawabannya tentu, ya, Don Quixote hidup dengan itu semua. Di titik ini perlu kita kembali pada pengarang, Seyyed Ahmad atau pada Miguel De Cervantes.
Hikayat ini, yang terpublikasi secara luas pada paruh abad pertengahan atau awal Renaisans menyuarakan pekik yang tajam pada revolusi. The Dark Age dalam hal ini menjadi momok dimana kemandegan terjadi bahkan dalam ranah-ranah spiritualitas. “Takhayul,” seperti dikatakan penyair Renaisans Francis; Voltaire mengungkapkan bahwa sedang “membakar dunia.” Bahwa tak ada celah dimana hidup manusia tanpa takhayul. Sialnya, takhayul ini tak mentransendensi pikiran ke ranah yang lebih ningrat, lebih tinggi. Ia meluluhlantakkan manusia menjadi makhluk pendamba kepatuhan buta, taklid yang tak asyik.
Di zaman itu, agama adalah kekuasaan. Spiritualitasnya hilang oleh ketamakan dan kehendak yang mencengkeram. Terkahir dari kampiun gila zaman tegang itu adalah Nietzsche yang segila Don Quixote dengan lakonnya yang gagah membakar berhala di alun-alun pasar: Zarathustra. Kelak, Zarathustra coba dibangkitkan dan dikembalikan ke gelanggang pasar oleh Herman Hesse di awal abad 20 demi mengingat satu hal yang luput dari manusia: bangkitnya tragedi yang sia-sia akibat perang dunia dan terdegradasinya manusia sedemikian rupa.
Oleh karena itu tak syak lagi bahwa Don Quixote sedang mengupayakan kesadaran dan iman. Kita juga melihat, cintanya Quixote pada Dulcienna melimpah tak bersebab tak berpangkal. Cintanya itu juga merupakan iman yang pancang pada pengabdian: atau kegaiban yang purna. Sedang kegilaannya mengiktibarkan pada kita bahwa hidup manusia bukan hanya sekedar hari-hari yang berulang tanpa gairah, tanpa isi.
Jika kisah ini dikontekstualisasi dengan realitas hari ini, bagaimana jadinya? Jika kemengulangan hari-hari sudah lagi tanpa ruh, jika iman telah lagi tanggal satu-satu, jika buku tak lagi seksi dan menarik untuk ditelaah dan dibaca, jika tak ada lagi penghayatan, wahyu menjadi perebutan kepentingan, cinta tak berpangkal pada spiritualitas dan pembebasan—singkatnya realitas banal tanpa kedalaman—apa yang harus kita lakukan? Saya sarankan kita perlu sedikit meniru Don Quixote De La Mancha.[]
Pernah Dimuat Di : Radar Sumedang.
Penulis : Syihabul Furqon












Posting Komentar